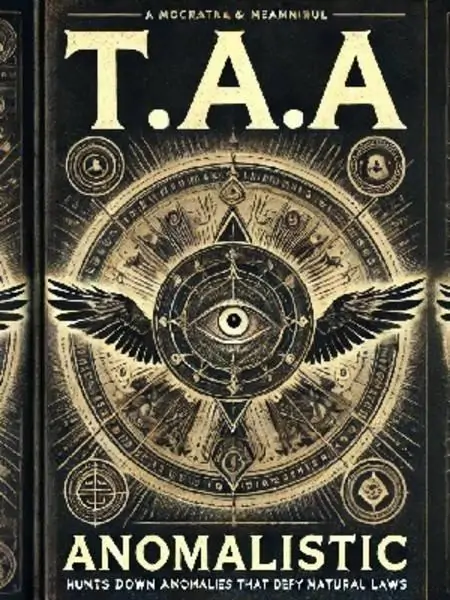
T.A.A Anomalistic
[ Pov 3 ]
04, januari, 1960
Di hutan yang rimbun dengan pepohonan yang menjulang tinggi, tiga anak kecil berusia sekitar tujuh sampai delapan tahun berlari tergesa-gesa dengan raut wajah ketakutan. Napas mereka terengah-engah di antara suara gemerisik dedaunan dan ranting yang patah. Setiap beberapa langkah, mereka tak henti-hentinya menoleh ke belakang, memastikan jarak dari bahaya yang ada di balik pepohonan.
Di belakang mereka, seekor monster dengan bulu putih selembut kapas, bergerak lincah dengan empat kaki yang tinggi. Panjang masing-masing kakinya sekitar 60 cm, dengan panjang tubuh sekitar dua meter, lebar tubuh satu meter, dengan hidung panjang dan kumis berwarna hitam, berkibar tertiup angin. Perawakannya mirip seperti tikus raksasa hanya saja jauh lebih menyeramkan dengan mata merah seperti bara api, memancarkan niat yang jelas untuk memangsa.
Saat anak yang paling belakang menoleh, kaki anak laki-laki itu tersandung batu yang tersembunyi di antara dedaunan, membuatnya terjatuh. Mata membelalak, seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Dia menyeret tubuhnya sejauh beberapa langkah, tapi gerakannya lambat.
Di depannya, tikus itu sudah ada di hadapannya. Sorot mata merahnya seperti predator yang siap menerkam mangsanya. Membuka mulutnya, memperlihatkan gigi lancip setajam silet yang mengkilau di bawah sinar bulan.
Dalam sekejap, tikus itu menerkam anak malang itu dengan brutal. Teriakan anak itu teredam saat tubuhnya dibanting keras ke tanah. Darah mengalir deras dari koyakan, membasahi baju dan tanah di sekitarnya. Matanya memudar, tetapi jari-jarinya masih bergerak untuk sesaat.
Kedua temannya hanya bisa menyaksikan temannya mati tanpa bisa melakukan apa-apa. Mata membelalak, berdiri membeku. Ketakutan membuat mereka menghentikan langkah sejenak, sebelum mereka kembali berlari, mencoba untuk menjauh dari monster yang telah menghabisi temannya.
Namun, tikus itu dengan cepat melompat dan menerkam anak laki-laki berambut coklat. Tikus itu menggigit lehernya, hingga hampir putus.
Anak yang selamat dengan cepat melarikan diri. Dia dapat merasakan pergelangan kakinya mulai lemas, jantung berdebar tak karuan, nafasnya terasa berat. Tapi dengan sekuat tenaga, dia berusaha keluar dari hutan.
Setelah peristiwa yang merenggut nyawa kedua temannya, anak laki-laki yang berhasil selamat segera memberi tahu orang tuanya tentang kejadian mengerikan yang baru saja ia alami. Kabar tentang keberadaan monster berperawakan tikus itu dengan cepat menyebar di kalangan penduduk desa. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, karena anak itu mengalami trauma yang begitu mendalam. Ketakutan yang menghantuinya membuatnya menutup diri dan enggan berbicara kepada siapa pun, meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban yang jelas.
...**********...
04, mei, 1960
Di desa yang aman, tentram dan damai, para warga desa biasa bercocok tanam di pagi harinya, udara segar dan sejuk yang menenangkan hati, awan biru yang indah, matahari bersinar ceria sejauh cakrawala. Namun,
semua itu berubah ketika malam hari.
Para warga desa mengunci rapat pintu dan tidak memperbolehkan anak-anak keluar pada malam hari. Warga yang mendapatkan tugas mengelilingi desa saat malam hari membawa senjata tajam, seperti celurit, golok, dan senjata tajam lainnya
...——————————...
***
[ ? PoV ]
Malam yang gelap, dihiasi jutaan bintang. Wanita berambut hitam bagaikan malam yang gelap, rambut terkucir ke belakang dengan cemas berjalan mondar-mandir. Aku tengah duduk di lantai yang tertutupi tikar, memperhatikan wajah Ibu yang penuh kecemasan.
"Bu, Bapak pergi dulu ya, bersama warga lainnya untuk memburu tikus yang meresahkan kita selama beberapa bulan ini."
Terdengar suara yang sangat familiar. Aku menoleh ke samping kanan dan melihat seorang pria berusia sekitar 30-an, berambut hitam, tangan kanannya memegang celurit.
Ibu menoleh, matanya penuh dengan khawatiran. Dia menghela nafas panjang, seakan mencoba untuk menenangkan diri.
"Pak, apa Bapak yakin mau pergi?" tanya Ibu, suaranya penuh dengan khawatiran.
"Yakin, Bu," jawab Bapak, berjalan mendekat ke arah Ibu.
Bapak memeluk Ibu dengan erat, tangannya mengelus punggung Ibu dengan lembut, dan penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, mereka berhenti berpelukan. Bapak memandang Ibu dengan mata yang penuh keprihatinan. Tangannya masih memegang bahu Ibu. Bapak menoleh ke arahku.
"Jangan nakal ya Satria, dengar kata Ibu," perintah Bapak kepadaku.
"Iya, pak," jawabku, berjalan menuju ke arah Bapak.
Aku memeluk perut Bapak dengan erat. Begitu menenangkan di tengah kekhawatiran yang melingkupi. Bapak mengusap kepalaku perlahan, menunduk sambil tersenyum tipis. Senyumnya selalu menenangkan, meskipun kali ini terasa lebih berat.
"Bapak pasti pulang, kan?" tanyaku sambil mendongak ke atas.
Bapak terdiam sejenak, seolah memikirkan kata yang tepat untuk di ucapkan. "Insya Allah nak, Bapak pasti pulang. Kamu jaga Ibu ya?"
Aku hanya mengangguk meski ada keraguan di dalam diriku. Tanganku memeluk perutnya lebih erat sebelum akhirnya melepaskannya. Bapak berbalik, menghela napas dalam, dan berjalan ke pintu. Ibu berdiri di belakangku, matanya mengikuti setiap langkah Bapak dengan tatapan cemas yang tidak bisa disembunyikan.
Pintu kayu itu berderit pelan saat dibuka; udara dingin malam menerobos masuk ke dalam rumah. Bapak melangkah keluar tanpa menoleh lagi, seakan tahu bahwa jika ia melihat kami sekali lagi, kakinya mungkin tak akan bisa melangkah lebih jauh.
Saat pintu kembali tertutup, keheningan yang mendalam menyelimuti ruangan. Ibu duduk di lantai, menarik napas panjang, dan mengusap matanya yang sedikit
mengeluarkan air mata.
"Ayo, nak, kita berdoa agar Bapak di beri keselamatan," ucap ibu, suara lebih stabil dari sebelumnya meskipun aku tahu bahwa didalam diri Ibu sangat khawatir.
Aku mengangguk, duduk bersila di samping Ibu. Di luar, terdengar suara-suara samar dari warga desa yang bersiap-siap; suara langkah kaki mereka berat.
Kami duduk dalam keheningan, hanya doa yang keluar dari bibir kami, sementara pikiran kami melayang pada Bapak yang kini telah bergabung dengan para warga yang lain.
Rasa kantuk mulai menguasai tubuhku. Aku tidur di pangkuan Ibu, memejamkan mataku dan berusaha tidur, namun pikiran tentang keselamatan Bapak di luar terus menghantui.
Aku berharap bahwa Bapak akan baik-baik saja di luar sana dan bahaya dari dalam hutan akan segera berakhir. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa banyak nyawa yang telah melayang akibat serangan tikus raksaksa itu.
.
.
.
Kilauan cahaya matahari yang masuk lewat jendela kamar membangunkanku dari tidur. Duduk di pinggir ranjang, mataku terasa masih berat. Menoleh ke luar jendela, sinar matahari dengan lembut menyentuh wajah dan lantai kamar, menciptakan bayangan hitam di atas lantai yang terbuat dari semen.
Aku turun dari ranjang dan berjalan keluar dari kamar, menuju ke dapur, melihat Ibu yang sudah bangun duduk termenung di meja makan. Wajah Ibu jauh lebih tua dari biasanya, tatapannya kosong, dan seisi ruangan sangat sunyi.
"Ibu," panggilku, berjalan mendekat ke arah Ibu.
Jari-jari kecilku mengguncang tangan Ibu beberapa kali. Ibu tersadar dari lamunannya. Raut wajahnya seperti terkejut, mata membelalak, alisnya dinaikkan ke atas sesaat, menoleh ke arahku dengan tatapan sayup-sayup.
"Bapak, sudah pulang?" tanyaku, memastikan.
"Belum, nak," jawabnya singkat, suaranya hampir seperti berbisik.
Jantungku berdetak sesaat. Perasaan gelisah semakin menguat. Malam sudah berlalu, dan Bapak belum kembali. Aku merasakan ada sesuatu yang salah, tapi aku berusaha menenangkan diriku.
"Kita tunggu sebentar lagi. Bapak pasti pulang," jawab Ibu, suara terdengar sangat pelan, mencoba menyakinkanku.
Aku hanya mengganggut. Tak berselang lama, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Aku bergegas membuka pintu, berharap Bapak berdiri di depan. Namun, saat pintu dibuka, bukan Bapak yang aku lihat, seorang pria, berambut hitam bagaikan kegelapan malam, mata
coklatnya bagaikan kayu yang dipoles dengan halus.
Sorot matanya lurus ke depan, alisnya sedikit berkerut, bibirnya menipis, tertarik ke bawah dengan rasa duka yang mendalam. Nama pria itu adalah Kumar, Pakdeku.
Pakde Kumar melirik ke arahku. "Satria, Ibumu mana?"
"Ibu, ada di dapur, Pakde," jawabku singkat.
"Tolong panggilkan Ibumu, ada yang harus dibicarakan," pinta Pakde Kumar kepadaku, suaranya sangat pelan.
Aku mengangguk, berjalan ke dapur, memberi tahu Ibu bahwa Pakde Kumar mencarinya. Ibu hanya mengangguk, bangkit, dan beranjak pergi dari dapur. Aku berjalan mengikuti langkah kakinya.
"Ada apa mas? Cari saya?" tanya Ibu, suara dibuat senatural mungkin.
Pakde Kumar, membuka suara. "Ini, Dek, ada yang mau saya sampaikan tentang ...."
Kata-kata Pakde Kumar berhenti di udara, seolah sedang memikirkan apa yang terjadi setelah ini.
"Tentang apa, mas?" tanya Ibu kembali, nada penasaran.
Pakde Kumar, menghela nafas panjang, tampak ragu-ragu, seolah menimbang beratnya kata-kata yang akan ia ucapkan. Ibu menunggu, wajahnya semakin pucat, sementara aku berdiri di samping, merasakan ketegangan yang merayap ke seluruh tubuhku.
"Suamimu, sudah meninggal," ucap Pakde Kumar, suaranya hampir seperti berbisik.
Angin berhembus sesaat masuk ke rumah kami. Untuk sesaat, keheningan tercipta. Waktu serasa berhenti. Mataku membelalak, mencoba memahami kata-kata yang keluar dari bibir pakde Kumar. Bapak meninggal? Tidak mungkin.
Ibu terpaku di tempat, wajahnya kosong, tidak ada emosi yang terlukis di sana, seolah otaknya menolak untuk mencerna apa yang baru saja didengar. Ia menatap Pakde Kumar. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata yang keluar.
"Mas," bisik Ibu, suaranya nyaris tidak terdengar. "Mas, becandakan?" tanya Ibu, tidak percaya dengan apa yang ia dengar.
Aku melihat bibir Ibu gemetar, kedua tangannya mulai terangkat ke mulut, menutupi getaran yang semakin jelas terlihat.
Pakde Kumar menundukkan kepalanya, tampak penuh duka dan penyesalan. "Dek, kamu yang sabar, ya."
Jantungku serasa berhenti berdetak. Napas terasa berat. Aku tidak ingin mendengar kelanjutan dari apa yang akan disampaikan. Tidak mungkin. Bapak pasti akan pulang. Dia berjanji padaku.
Suara tangisan Ibu pecah, air mata keluar dari balik kelopak matanya, mengalir sampai ke dagu. Dia jatuh berlutut, kedua tangannya memegang kepala, air mata membasahi wajahnya.
Aku hanya bisa berdiri beku, menatap pemandangan yang tak pernah kuharapkan terjadi. Air mata mulai memburamkan pandanganku dan menetes di lantai. Rasanya ingin berlari ke pelukan Ibu, tapi kakiku seakan tertancap di lantai. Kepalaku penuh dengan kata-kata Bapak semalam, janji bahwa ia akan pulang.
Duka yang mendalam menggantung di udara, Pakde kumar hanya berdiri di luar pintu, lidahnya tidak mengeluarkan sepatah kata pun.
Ibu, yang kini berlutut di lantai, terus menangis, seakan dunia di sekitarnya runtuh. Tangisannya begitu lirih namun penuh kesedihan, suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tubuhnya gemetar tak terkontrol, dan kedua tangannya mencengkeram kuat rambutnya, menahan beban rasa kehilangan yang begitu berat.
Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tidak keluar dari mulutku. Perasaanku hampa, seluruh tubuhku mati rasa. Dadaku sesak, tapi aku tidak menangis. Aku hanya berdiri, memandang Ibu yang tersungkur di lantai, merasakan sakit yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa kuakhiri.
.
.
.
Suara tanah yang dilempar ke dalam liang lahat terdengar samar, berbaur dengan isak tangis ibu yang tak henti-hentinya menggema di udara. Setiap gumpalan tanah yang jatuh membuat perasaan di dadaku semakin berat, seolah tanah itu juga menutupi hatiku. Aku berdiri di samping Ibu, memegang erat ujung bajunya, mencoba menahan tangis yang terus mendesak keluar, namun mataku sudah sembab, tak ada lagi air mata yang tersisa.
Warga desa yang berkumpul di sekitar kuburan bapak, mereka mengucapkan lantunan doa di dalam hati. Ibu masih tersedu di samping liang lahat, tubuhnya limbung, seperti akan jatuh kapan saja. Seorang tetangga, Bu Yanti, mendekat dan mencoba memeluk Ibu, berusaha menenangkannya.
"Yang sabar ya Bu ... Ini sudah takdir," ucap Bu Yanti,
mencoba menenangkan.
Setelah beberapa saat, warga desa mulai meninggalkan area pemakaman satu per satu, mengucapkan belasungkawa dengan wajah yang penuh rasa simpati. Aku hanya berdiri di sana, memandangi gundukan tanah yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir bapak. Sungguh, aku tak pernah menyangka bahwa bapak akan pergi secepat ini. Kenangan bersama Bapak berputar di benakku, mulai dari tawa hangatnya, nasihat bijaknya, hingga senyum lembut yang selalu ia berikan sebelum pergi bekerja.
Tangan kanan Ibu mengelus gundukkan tanah dengan lembut, setetes air mata jatuh mengenai gundukkan tanah.
"Pak, ibu pergi ya. Bapak yang tenang di alam sana, kelak kita akan dipertemukan lagi di akhirat," ucap Ibu, suaranya sangatlah pelan.
Kami berjalan pergi dari kuburan Bapak, langkah kami terasa sangat berat. Setiap beberapa langkah, aku terus menoleh ke gundukkan tanah, jari-jari kecilku, menggenggam erat di tangan kiri Ibu.
.
.
.
Di depan mataku, melihat sebuah rumah sederhana berbahan kayu, berdiri kokoh. Suara nyaring, saat pintu dibuka, terdengar jelas di telingaku, memperlihatkan isi dalam rumah. Suasana sangat hening, tak siapapun di rumah. Mataku tertuju pada sofa yang terletak di ruang tamu. Sofa tua yang dulu sering digunakan Bapak untuk duduk setiap malam sepulang dari bekerja, menghabiskan waktu dengan membaca koran atau sekadar berbincang ringan dengan Ibu. Kini, sofa itu terlihat kosong, hanya menyisakan kenangan tentang kehangatan yang pernah ada di rumah ini.
Melirik, wajah Ibu. Mata Ibu memerah, suara ingus yang di tarik kembali ke dalam hidung, terdengar jelas di telingaku.
"Rumah ini tampak sepi," ucap ibu. "Sekarang Bapak sudah tidak ada." Mata merah Ibu, menyapu setiap sudut rumah.
Mengeratkan tangan kiriku, aku menarik napas dalam, mataku terbelalak. Api kebencian berkobar di dalam hatiku. Monster itu telah merenggut sosok yang aku sayangi. Monster itu juga yang membuatku kehilangan kedua temanku, dan menghancurkan sahabat dekatku, yang kini hanya bisa melamun setiap hari, pikirannya hancur, jiwanya terganggu.
Mengeratkan tangan kiriku lebih kuat lagi, aku merasakan setiap kuku-kukuku, menekan telapak tanganku hingga hampir menembus kulit.
.
.
.
Sejak kehilangan Bapak, hidup kami tak pernah sama. Kehampaan yang ditinggalkan terasa begitu nyata di setiap sudut rumah. Meski ibu berusaha tegar, aku tahu luka itu masih menganga, terutama saat malam tiba, ketika kesunyian terasa lebih mencekam.
Dua bulan telah berlalu sejak kematian Bapak. Kami berdua perlahan mencoba untuk mengikhlaskan Bapak, meskipun terkadang, kami seakan bisa merasakan bahwa Bapak masih ada di sisik kami.
Saat ini, kami berada di kuburan yang sama tempat Bapak dimakamkan, tapi kali ini, untuk seorang warga desa lainnya yang menjadi korban kesekian kalinya dari monster kejam itu. Jasadnya di temukan tidak utuh;
tangan kanan dan kaki kirinya hilang.
Terdengar suara adzan dari salah satu warga yang turun ke liang lahat, yang masih kosong, setelah adzan mereda, hanya isak tangis yang menggema di udara, angin sore menerpa wajahku.
Seorang laki-laki yang lebih tua dari para penggali kubur mengangkat tangan, memberikan isyarat kepada para pengusung jenazah untuk menurunkan jenazah ke liang lahat. Pelan-pelan, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat.
Setelah jenazah selesai dimakamkan, keluarga korban menaburkan bunga di atas gundukan tanah. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air mata.
Setelah proses pemakaman selesai, aku memperhatikan sekelilingku. Wajah-wajah yang muram, suasana penuh duka serasa menyesakkan. Tanpa kusadari, pikiranku melayang, teringat semua peristiwa mengerikan yang telah terjadi. Monster itu masih bebas berkeliaran, dan kami hanya bisa menunggu korban berikutnya. Aku mengepalkan tangan, merasa begitu lemah.
...——————————...
***
[ poV 3 ]
Di tempat yang berbeda, jauh dari suasana pemakaman, seorang pria duduk di tepi jendela, menatap gelapnya malam. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, tapi pikirannya melayang jauh dari kenyamanan ruangan.
"Tampaknya, aku tidak bisa mengatasi semua kejadian supranatural ini seorang diri," gumamnya, menatap keluar dari balik jendela.
[ Request dari Kia Writer ]
[ ? poV ]
Membuka jendela balkon, cahaya matahari dengan lembut menyentuh wajahku. Mentari bersinar ceria, langit biru yang indah dengan awan putih sebagai pelengkapnya. Aku duduk di kursi, membalik buku harian yang ada di tanganku, mengambil pena yang aku sisipkan di telinga, dan mulai menulis. Tapi kali ini, aku tidak menulis keseharianku, melainkan menulis kejadian di masa lalu, saat di mana aku mendapatkan kekuatan untuk membaca pikiran orang lain hanya dengan kontak mata, dan pengalaman déjà vu yang terasa begitu nyata. Waktu itu, aku masih duduk di bangku sekolah dasar, sekitar kelas 4 SD.
...——————————...
Awal mula kekuatan ini muncul dari mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di suatu tempat yang asing, sebuah ruang putih yang luasnya sejauh cakrawala. Semuanya begitu terang, seperti berada di tengah cahaya yang tak berujung.
Mataku menyapu segala arah, memperhatikan setiap sudut ruangan kosong ini. Tiba-tiba, seorang gadis muncul, berdiri di hadapanku. Rasanya seperti melihat diriku sendiri dalam cermin. Dia tersenyum, senyum yang aneh dan samar; matanya memandang langsung padaku.
Tangan kanannya terulur, mencoba menggapai wajahku. Saat itu juga, tubuhku terasa membeku, seolah-olah terperangkap dalam es yang tak terlihat.
Aku terbangun dari tidurku. Jantungku berdebar kencang bagaikan genderang perang. Mata membelalak, menatap ke arah jam dinding yang tergantung tepat di atas pintu kamar. Waktu menunjukkan pukul dua dini hari.
Keringat mengalir dari dahiku, suara nafasku terdengar berat dikesunyian malam dan mataku terasa berat. Aku mencoba mengabaikan mimpi itu dan kembali tidur, tapi ternyata malam itu adalah awal dari segalanya.
.
.
.
keesokan harinya, di sekolah, ada sesuatu yang terasa berbeda. Setiap kali berbicara dengan teman-temanku, suara-suara aneh mulai terdengar di kepalaku.
Saat guru berjalan memasuki ruangan kelas, terlihat seorang wanita berambut pirang bagaikan benang sutra, dengan mata biru yang indah bagaikan lautan. Rambutnya terurai ke belakang, berjalan dengan anggun. Wanita yang berusia sekitar 20-an itu berdiri di hadapan kami. Nama wanita itu adalah Elaina, guru matematika kami.
...Ilustrasi Elaina....
"Selamat pagi anak-anak," sapa Bu Elaina kepada para siswa.
"Pagi Bu!" balas kami serempak, dengan semangat yang sedikit terpaksa.
Saat aku menatap mata birunya Bu Elaina yang begitu dalam, sedalam samudra yang tak berujung, suara itu kembali terdengar. Namun kali ini berbeda.
"Sampai sekarang, belum ada kabar dari tim yang ditugaskan untuk menangkap anomali yang berhasil melarikan diri dari sel penahanannya."
Aku tersentak. Apa? Anomali? Sel penahanan? Otakku berputar mencari arti dari kata-kata itu. Apakah itu, suaranya guru Elaina. Tapi Bagaimana mungkin hal seperti ini ada di kepala seorang guru matematika?
"Apa kalian sudah siapa untuk belajar?" tanya wanita berambut pirang, tersenyum manis seperti biasa.
"Tidak!" seru kami hampir serempak, dengan keberanian yang entah datang dari mana.
"Kenapa kalian tidak siap belajar?" Bu Elaina tampak bingung.
"Karena matematika itu membingungkan, bu! Rasanya kepalaku mau meledak!" teriak seorang teman sekelas dengan nada bercanda yang sedikit memanas.
Guru Elaina tersenyum tipis sambil memandang kami. Lagi-lagi, suara aneh terdengar kembali di kepalaku.
"Mereka ini benar-benar lucu."
Aku mulai merasakan ada pola di sini. Suara yang kudengar itu pasti berasal dari pikirannya Bu Elaina. Tapi bagaimana mungkin? Apakah aku benar-benar bisa membaca pikiran orang lain?
"Ok, sekarang mari kita mulai pelajarannya," ucap Bu Elaina. Mengambil kapur yang ada di meja. "Siapakan alat tulis kalian ya," ucap Bu Elaina, berbalik menghadap papan tulis. Bu Elaina menuliskan sesuatu di papan kapur. 'Taksiran atas dari 98 x 46 adalah...'
"Apa ada yang bisa menjawab soal ini?" tanya Bu Elaina,
membalikkan badannya dan menatap para siswa.
Tidak ada yang berani menjawab soal yang di berikan Bu Elaina, keheningan memenuhi seisi kelas. Karena tidak ada yang punya nyali untuk menjawab soal, Bu Elaina kembali membalikkan badannya di papan kapur, seakan ingin menerangkan.
"Cara mengerjakan soal ini adalah," Bu Elaina mulai menulis. "98 dibulatkan ke atas menjadi 100 dan 46 dibulatkan ke atas menjadi 50. Jadi taksiran 98 x 46 \= 100 x 50 \= 5.000."
.
.
.
Suara bel berbunyi, menggema di udara, terdengar jelas di telinga, menandakan jam istirahat telah dimulai. Guru Elaina kemudian membereskan buku-buku yang ada di meja dan menatap ke arah kami.
"Sekarang kalian boleh istirahat. Ingat, jangan lupa untuk mengerjakan PR. Sampai ketemu lagi minggu depan," ujar Guru Elaina, sambil mulai berjalan keluar kelas. "Jika sampai minggu depan kalian tidak mengerjakan PR, maka akan ada hukum cinta untuk kalian."
"Lisa!" Setelah Bu Elaina keluar dari kelas, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku.
Aku menoleh ke arah sumber suara, melihat anak laki-laki berambut hitam bagaikan bulu gagak, mata coklatnya bagaikan dua biji kopi hangat, menggoda dan menenangkan. Nama anak itu adalah Thomas, teman sekelasku yang duduk di bangku sebelah. Dia tersenyum, mencoba menarik perhatianku.
"Ada apa Thomas?" tanyaku kepada anak itu.
"Apakah kau paham dengan soal matematika yang diberikan Bu Elaina?" tanya Thomas kepadaku.
Aku mengangguk. "Iya, aku ngerti. Kamu sendiri gimana?"
"Sudah tentu aku paham," jawab Thomas, nada penuh percaya diri. "Padahal aku sama sekali gak paham dengan apa yang disampaikan oleh Bu Elaina."
Lagi-lagi, aku mendengar suara itu. Tapi, bila didengar dengan baik, suara itu mirip sekali dengan Thomas.
Aku mengerutkan dahi. "Yakin, kamu ngerti?" tanyaku kembali, mencoba memastikan apa yang kudengar.
"Ya-yakin," jawabnya dengan terbata-bata.
Aku terdiam sejenak, menatap Thomas dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku merasa aneh dan bingung. Pikiran orang lain berputar-putar di kepalaku seperti suara radio yang tidak bisa kuatur. Namun, di sisi lain, aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan.
Ketika aku menatap matanya lagi, suara di kepalaku kembali terdengar. "Semoga saja dia tidak tahu kalau aku bohong."
Kalimat itu muncul begitu saja tanpa ada yang mengucapkannya. Seketika tubuhku terasa dingin. Jantungku berdebar lebih kencang. Suara-suara ini nyata, bukan sekadar khayalan atau firasat aneh. Aku benar-benar bisa mendengar pikiran orang lain.
"Thomas," ucapku pelan, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. "Kau bohong, kan?"
Matanya membelalak, jelas sekali ia terkejut dengan pertanyaanku yang tiba-tiba. "Eh, apa maksudmu?" suaranya terdengar gugup.
Aku menghela napas, menenangkan diriku. "Kau bilang kau mengerti soal matematika tadi, tapi aku tahu kau tidak paham. Kau membohongiku."
Thomas menundukkan kepala, menggaruk belakang lehernya dengan canggung. "Oke, mungkin aku sedikit tidak paham," akunya, suara lemah. "Tapi ... bagaimana kau tahu?"
"Aku hanya tahu." Aku tersenyum tipis.
Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Apa yang harus kukatakan padanya? Aku tidak ingin membuatnya takut atau membuatnya berpikir aku aneh. Rasanya tidak mungkin bagiku untuk mengaku bahwa aku bisa mendengar pikirannya.
Tangan Thomas, mengambil buku yang tergeletak di meja dan memasukkannya di tas. "Yah, terserahlah," katanya sambil tersenyum. "Aku akan coba pahami nanti di rumah."
Aku melihat Thomas beranjak dari tempat duduknya, berjalan menuju pintu kelas dengan langkah ringan. Sementara itu, kepalaku penuh dengan pertanyaan yang berputar-putar. Bagaimana mungkin aku bisa mendengar pikiran orang lain hanya dengan menatap matanya? Apakah ini hanya kebetulan atau benar-benar kemampuan yang kumiliki?
Saat Thomas semakin menjauh, suara-suara di kepalaku menghilang. Rasanya seolah ada tombol yang mematikan semua kebisingan saat aku tak lagi menatap mata orang lain. Jadi, ini bukan sekadar firasat. Aku benar-benar bisa membaca pikiran orang melalui kontak mata.
Aku berdiri, memasukkan buku ke dalam tas, dan berjalan keluar kelas, melewati kerumunan siswa yang bergegas ke kantin atau lapangan. Rasanya aku seperti terjebak di dalam gerombolan semut.
Saat sampai di koridor sekolah yang sepi, aku berhenti sejenak, bersandar ke dinding dan menatap ke lantai. Bagaimana kalau orang lain tahu tentang ini? Apakah mereka akan menganggapku aneh? Atau bahkan takut padaku? Pikiran itu membuat dadaku terasa sesak.
Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat seorang gadis berambut hitam yang terurai ke belakang, bermata hitam bagaikan lautan terdalam, tidak ada sinar yang menerangi. Dia berjalan pelan ke arahku. Namanya Rika Orimoto, siswi pindahan dari jepang dan teman sekelasku yang terkenal pendiam. Dia jarang berbicara dengan siapapun, tapi matanya selalu tampak tajam, seolah-olah dia sedang menilai seseorang.
Rika berhenti di depanku, matanya tertuju langsung padaku. Tatapannya begitu tajam, sampai menusuk ke jiwaku, tubuhku dibuat merinding karena tatapannya. Tanda sadar, aku menatap matanya, dan saat itu juga, suara-suara kembali menyeruak ke dalam pikiranku.
"Kau dan aku adalah sama."
Jantungku berdebar kencang. Dia tahu? Bagaimana mungkin? Aku memalingkan pandanganku secepat mungkin, mencoba menghindari kontak mata lebih lama.
Rika mengerutkan dahinya, seolah dia tahu sesuatu. "Lisa," suaranya begitu tenang, tapi ada nada sedikit misterius di dalamnya. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu."
Aku terdiam. Bingung, harus merespon apa. "B-bicara soal apa?" tanyaku, mencoba terdengar biasa saja.
Dia menghela napas pelan, matanya tetap menatapku meskipun aku menghindari pandangannya. "Kau merasa aneh, kan, pagi ini?"
Kata-katanya membuat aku membeku di tempat. Bagaimana dia bisa tahu? Aku belum mengatakan
sesuatu kepada siapapun. Dia memandangku lekat-lekat, berjalan mendekat dengan langkah ringan. Rika mendekatkan bibirnya di telingaku.
"Kita tidak sendirian ... 'Mereka' selalu mengawasi."
Kata-katanya membuat bulu kudukku meremang. Nafasku berhenti sesaat, seolah udara di sekitar menghilang dalam sekejap mata. 'Mereka' apa yang dimaksud Rika? Tubuhku terasa terpaku di tempat, seperti ditancapkan oleh sesuatu. Rika berjalan mundur sedikit, memperhatikan ekspresiku dengan mata yang dingin dan menusuk jiwa.
"Kau pasti keheranan. Tapi kau akan mengerti maksudku, ketika sudah waktunya." Rika tersenyum tipis. Sekilas, aku melihat gambar jarum jam muncul di belakang Rika. Rasanya, tubuhku seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat.
Rika berjalan melewatiku, langkahnya ringan dan tak bersuara. Ingin rasanya, aku bertanya apa maksud dari kata 'Mereka' tapi lidahku kelu, tak mampu berkata apa-apa. Kata-kata itu seakan tersangkut di tenggorokanku, tertahan oleh rasa takut dan kebingungan yang membelenggu pikiranku. Rika berlalu begitu saja, meninggalkanku dalam keadaan terpaku, sementara jarum jam itu terus membayang di benakku.
Aku menoleh ke arah di mana Rika baru saja lewat, namun dia sudah menghilang di antara koridor sekolah yang panjang. Apakah yang tadi kulihat nyata? Ataukah hanya imajinasiku?
Dadaku terasa sesak, sementara pikiranku berputar-putar, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Sekilas, aku teringat kembali tentang mimpiku semalam, ruang putih, gadis yang mirip denganku, dan tatapan yang seakan menembus diriku. Apakah semua ini saling berhubungan?
Sementara aku masih terdiam, tiba-tiba terdengar suara bel tanda jam istirahat selesai. "Tunggu, bukankah istirahat baru saja dimulai." Kebingungan melanda pikiranku. Bel istirahat baru saja berbunyi beberapa menit yang lalu, tapi sekarang sudah berbunyi lagi? Aku melihat ke arah jam dinding di koridor sekolah, dan yang kulihat membuatku semakin bingung. Jarum jam menunjukkan waktu yang seharusnya tak mungkin. Sudah hampir satu jam berlalu sejak istirahat dimulai, tapi aku merasa baru saja berdiri di sini, terpaku, tidak lebih dari beberapa menit.
Jantungku mulai berdebar kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Seperti waktu telah melompat, meninggalkanku tanpa peringatan. Apa yang sedang terjadi.
Aku bergegas masuk kembali ke kelas, tapi suasana di dalam ruangan terasa ganjil. Semua orang diam, tidak ada percakapan, tidak ada suara langkah kaki atau tawa yang biasa terdengar saat para siswa kembali setelah istirahat. Setiap orang duduk di tempat mereka, kepala tertunduk seperti sedang merenung dalam keheningan.
Mataku tertuju pada bangku Rika. Kosong.
Kakiku melangkah pelan menuju tempat dudukku, tapi perasaan janggal ini semakin kuat. Saat aku duduk dan menatap ke depan, jantungku nyaris berhenti. Di papan tulis, dengan kapur putih, tertulis sesuatu.
..."Kau akan tahu siapa 'Mereka' ketika waktunya tiba."...
Tanganku gemetar. Tulisan itu jelas bukan dari guru mana pun. Siapa yang menulisnya? Dan apa maksudnya? Saat aku sedang menatap tulisan itu dengan kebingungan yang mendalam, tiba-tiba ada suara lembut yang memecah keheningan di kepalaku, suara yang tidak asing. "Jangan takut, Lisa. Kita akan bertemu lagi."
"Itu suara Rika." Memutar kepalaku ke segala arah untuk mencari sumber suara. Tapi aku tidak melihat apapun.
"..."
"Hei! Lisa."
Aku tersentak, suara Thomas menarikku kembali ke realitas. Mataku masih tertuju ke papan tulis, tapi sekarang tulisan aneh itu sudah hilang. Tidak ada jejak kapur yang tersisa, hanya deretan angka dan soal matematika biasa yang ditulis guru Elaina tadi.
"Hei, Lisa. Kamu kenapa? Kok bengong aja?" Thomas berdiri di samping mejaku, mengerutkan dahi dengan ekspresi bingung.
Aku memutar kepalaku, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Perasaan deja vu menyeruak, seolah semua yang kulihat ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Setiap detil—sikap Thomas, suasana kelas, bahkan hembusan angin dari jendela—terasa familiar, tapi anehnya, seolah ada sesuatu yang hilang atau terlewat.
"Aku ... aku nggak apa-apa," jawabku pelan, berusaha menyembunyikan kebingungan.
Thomas masih menatapku dengan sedikit heran. Memalingkan pandanganku dari Thomas, mataku kembali menatap papan tulis yang kosong, dan pikiran-pikiran aneh mulai merasuki benakku. Siapa 'Mereka'? Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
...——————————...
"Hei, Lisa apa yang kau tulis?"
Aku tersentak sedikit, menghentikan gerakan tanganku yang sedang menulis. Aku menoleh ke kanan, dan di sana berdiri temanku, Elana. Rambut cokelatnya yang lembut dan halus, mata hijau zamrud yang berkalau. Dia berdiri di depan pintu, tersenyum hangat padaku.
"Seperti biasa, aku sedang menulis di buku harianku, Elana," jawabku sambil menutup buku.
"Apa kau sudah selesai menulisnya? Kalau sudah selesai, bisakah kau menemaniku berbelanja ke supermarket?" tanya wanita bermata hijau zamrud kepadaku.
...Ilustrasi Elana....
"Tentu saja." Aku menaruh buku harianku di meja, bangkit dan berjalan mendekat ke arah Elana.
.
.
.
***
[ ? PoV ]
Aku melangkah menyusuri lorong supermarket. Tatapanku tajam, menyapu setiap barang di rak. Jam di pergelangan tangan kananku bergetar dan mengeluarkan suara bip yang khas.
"Anomali," gumamku, hampir seperti berbisik.
Mata berputar mencari sumber gangguan. Pandanganku terkunci pada dua wanita yang berdiri sekitar 5 meter dari tempatku berada. Aku segera berbalik, berjalan cepat menuju tempat yang lebih sepi.
Aku berjalan keluar dari supermarket dan mencari tempat yang sepi untuk menghubungi markas T.A.A.
Aku menekan layar jam tanganku, mendekatkan layar jam ke bibirku. "Ini aku, Agen 10, melaporkan kepada markas Anomalistic bahwa telah ditemukan anomali berwujud manusia."