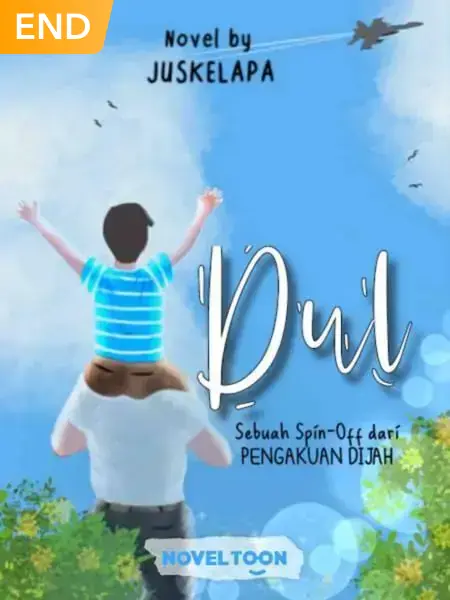
Dul
Novel berjudul DUL ini adalah spin-off dari novel PENGAKUAN DIJAH, bergenre drama dan rating 13+ serta bisa dibaca oleh semua usia.
Pastikan memilih bacaan yang tepat, berkomentar cerdas dan santun untuk menunjukkan identitas kita, serta menyadari bahwa semua cerita dalam novel hanyalah penuturan subjektif dari penulis.
Selamat datang di dunia imajinasi juskelapa.
*****
Munculnya ingatan Dul terpisah-pisah. Beberapa potong ingatan indah tersimpan rapi dan ingin terus dikenangnya. Ingatan tak mengenakkan yang ingin dilupakan, juga tersimpan rapi. Meski ia ingin membuang ingatan buruk, ingatan itu seakan ingin bertahan agar bisa tetap membuatnya takut.
Sekali waktu ia mengingat percakapan kecil yang dilakukannya bersama sang ibu. Walau ia jarang menjawab dan tak mengerti apa yang dibicarakan, ibunya kerap selalu berbicara. Dul hanya diam mendengar. Ia menganggap, dengan mendengar ibunya berbicara, hal itu bisa menghilangkan gurat lelah di wajah cantik wanita itu.
Ingatan pertama yang muncul di benak Dul adalah saat mendengar suara pisau beradu dengan talenan. Dul merasa tubuhnya sedikit terguncang-guncang. Ia setengah terkantuk-kantuk, dan terikat ke tubuh ibunya dengan sebuah jarik. Saat membuka sedikit mata, Dul menyadari mereka sedang berada di dapur. Ia sedikit menelengkan kepala untuk melihat apa yang sedang dikerjakan ibunya. Setelah melihat wortel dan buncis yang dipotong-potong, Dul menyadari kalau wanita itu akan merebus semua sayuran ke dalam panci dan menyemplungkan beberapa potong kecil ayam.
“Masak sop ayam?” tanya Dul dengan suara parau kekanakan.
“Biar kamu cepat sembuh,” sahut Dijah.
Orang-orang kerap memanggil ibunya dengan sebutan Dijah. Dul belum tahu nama panjang perempuan yang melahirkannya saat itu. Di usia itu, nama baginya bukan masalah. Permasalahan bagi Dul saat itu adalah ia ingin tinggal dan tidur di dekat ibunya.
“Badan kamu masih panas, dari tadi ngelindur terus. Jadi Ibu gendong. “Sekarang, apanya yang sakit?” tanya Dijah lagi.
“Badan,” sahut Dul pendek. Tak menjelaskan dengan rinci seperti apa sakit di badannya. Ibunya pasti sudah tahu, pikirnya.
“Kita ke depan dulu. Kamu baring sebentar biar Ibu siapin sop-nya. Mbah Wedok belanja ke pasar. Mbah Lanang enggak usah ditanya. Katanya ke warung sebentar, tapi udah dua jam enggak pulang-pulang. Mungkin sekalian ngopi dan main catur. Taunya ngomel terus. Katanya kemarin malem kamu rewel sampai Mbah Lanang enggak bisa tidur." Dijah merentangkan kasur busa menggunakan kaki, lalu duduk perlahan memindahkan Dul dari gendongan.
“Aku mau sekolah,” ucap Dul.
“Belum bisa. Tahun depan baru masuk TK. Baring di sini,” kata Dijah, menurunkan Dul dengan perlahan.
“Ibu tidur di sini. Jangan pulang,” ucap Dul lagi. Malam itu ia benar-benar ingin ditemani ibunya. Kemarin malam ia bermimpi buruk dan teringat bahwa ia terbangun dengan sisa lengkingan di tenggorokan. Ia mengigau. Mbah Lanang marah dan mengomelinya agar kembali tidur.
Saat Dul meletakkan kepalanya ke bantal, ibunya berhenti untuk menatap. Ibunya terlihat cantik sekali, pikir Dul. Meski kaus yang dikenakan ibunya berleher kendur, rambutnya terikat sederhana, dan wajahnya terlihat sangat lelah.
“Ya, udah … malem ini Ibu nginep di sini. Kita bisa tidur di depan tv berdua. Kalau kamu enggak bisa tidur, nanti Ibu puterin film kartun. Sekarang baring dulu. Ibu mau beresin masakan,” kata Dijah.
Dul langsung bergulung mendekap guling kecil semasa bayi yang masih ia gunakan. Guling kempes dan memiliki aroma khas buatnya.
Malam itu adalah kenangan di mana Dul merasa begitu bersalah pada ibunya. Malam penyebab luka yang tak pernah sembuh. Karena ia yang terlalu memaksa meminta ibunya menginap di rumah mbahnya. Untuk kali pertama, ia melihat ibunya dipukuli mati-matian.
Mereka baru saja meletakkan kepala di bantal. Berdua berpelukan menonton sisa acara televisi yang hampir selesai di pukul sebelas malam. Dul berbaring miring, punggungnya baru ditepuk-tepuk pelan agar ia bisa segera tertidur. Lalu mereka dikejutkan dengan gedoran pintu depan dan suara teriakan laki-laki yang memanggil ibunya.
Itu suara bapak Dul. Namanya Fredy. Bapak kandung yang sudah sangat lama berpisah dari ibunya.
“Dijah ...! Aku tau kamu di dalam! Keluar! Aku perlu teman tidur!” teriak Fredy.
Dul melirik ibunya. Dijah meletakkan telunjuk di depan bibir meminta Dul untuk tetap diam. Tapi ternyata beberapa menit berpelukan dalam diam, tak membuat Fredy percaya.
Beberapa detik yang terasa lama, suara di luar kembali senyap. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Lalu bersamaan ibu dan anak itu melihat kilatan api dari celah tipis pintu kayu yang sudah sepuh.
“Aku bawa obor! Mau tak bakar rumah ini kalau kamu enggak keluar! Biar habis sekalian!” jerit Fredy lagi.
Dengan matanya yang cekung, Dul mengerti apa yang dimaksud bapaknya. Di usianya, dia cukup mengerti kalau api itu bisa melahap seluruh rumah dan mencelakakan mereka semua.
“Kurang ajar! Kamu jangan keluar,” pinta Dijah pada Dul. “Pak! Bapak! Bangun! Itu Fredy dateng mau bakar rumah!” teriaknya lagi.
Lima menit kemudian bapak Dijah keluar dari kamar. Menggaruk-garuk kepalanya masih dengan mendekap kain sarung. “Ada apa lagi? Kamu pasti ngomong yang enggak-enggak makanya dia ngamuk.”
“Ngomong enggak-enggak gimana? Aku dari siang di rumah nemenin anakku. Dari tadi juga belum bisa tidur karena Dul masih panas. Bapak yang keluar. Suruh dia pergi. Malu sama tetangga,” kata Dijah.
Kejadian itu sangat cepat di mata Dul. Pintu dibuka sedikit dan Mbah Lanang bicara dengan sangat halus pada pria di depan pintu. Hanya selang beberapa detik, pria mengerikan itu menghambur ke dalam dan menarik paksa ibunya keluar. Sebuah tongkat kayu dengan api menyala terayun-ayun di tangannya.
“Ibu …! Ibu …!” Dul terhuyung-huyung berdiri mau menyongsong ibunya. Mbah Lanang menarik tubuhnya masuk, dan Mbah Wedok menangis seraya merangkak di lantai karena lututnya lemas.
Dalam sekilas pandangannya ke luar tadi, tampak olehnya ibu yang begitu dia harapkan menemani tidur, bergumul dengan laki-laki yang berusaha menciumnya.
Dul merasa tenggorokannya panas bagai menelan api yang terlempar tak jauh dari ibu dan bapaknya. Dia mau membantu ibunya, tapi badan yang kurus bisa ditahan dengan mudah oleh Mbah Lanang yang berdiri meneriaki bapaknya.
“Tolong! Bapak …! Tolong!” jerit ibunya. “Dia mau perrkosa aku! Bapak …!”
Jeritan ibunya memecah keheningan malam itu. Dua tetangga pria berhasil melerai. Tak dilihat olehnya bagaimana ibunya berhasil melepaskan cengkeraman dari pria mengerikan itu. Ibunya masuk kembali ke rumah dengan rupa yang sangat kotor. Kerah kausnya melorot, rambutnya awut-awutan dan berpasir. Telapak tangan ibunya membekap mulut.
“Udah—udah, kamu jangan nangis lagi. Nanti luka Ibu jadi sakit,” kata Dijah, menyeka bibirnya yang sedikit robek karena membenturkan mulut saat hendak dicium paksa oleh Fredy.
Dul masih menangis. Duduk di atas kasur tipis sambil mendekap gulingnya. Tanpa ia menangis pun, luka itu pasti sangat sakit. Ia meyakini bahwa dialah penyebab ibunya babak belur malam itu.
“Bu … jangan nginep di sini lagi.” Dul mengelap air mata dengan leher kausnya.
Dengan ingatan seorang kanak-kanak yang terbatas, Dul mengingat bagaimana Mbah Lanang menganggap biasa luka-luka ibunya. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat bagaimana Mbah Wedok tak menyampaikan sedikit pun penghiburan pada ibunya. Ibunya sendirian. Ibunya benar-benar sendirian. Ia menangis untuk ibunya.
Dul mengamati bagaimana ibunya dengan cekatan merawat luka sendiri. Bahkan tak ada rintihan atau keluhan yang keluar dari bibir yang terluka itu. Karena sorot matanya yang tak lepas memandang sang ibu, akhirnya wanita itu mendongak.
“Kalau sudah besar, jangan perlakukan perempuan begini, ya, Dul. Kamu harus jadi anak hebat,” kata ibunya.
Dul tak menjawab. Kepalanya menunduk mengambil sehelai kapas untuk membantu menyeka sisa darah di bibir ibunya. Dalam kepalanya ia sudah membayangkan bagaimana cara menyingkirkan pria yang membuat ibunya menderita.
To Be Continued
Ingatan lain yang membekas di pikiran Dul adalah saat ibunya datang dengan raut cemas. Ibunya keluar masuk rumah seakan ingin menyampaikan sesuatu pada Mbah Wedok yang duduk di dapur sambil mengupas ubi. Walau ibunya berkali-kali lewat, mbahnya tak sedikit pun bertanya. Ibu dari ibunya itu seakan sangat larut dalam pekerjaannya.
“Bu,” panggil Dijah, mendekati ibunya.
“Mmmm?”
“Besok aku mau daftarin Dul masuk TK. Brosurnya udah aku ambil jauh-jauh hari. Tapi uangku kurang. Kurang seratus ribu, Bu. Kalau Ibu ada simpenan uang yang selama ini aku kasih, boleh aku pakai dulu? Nanti aku ganti dalam beberapa hari ini. Ada?” Dijah berjongkok di sebelah ibunya.
“Uang Ibu enggak ada, Jah. Yang kamu kasih setiap hari habis buat belanja. Buat jajan Dul juga," kata ibunya.
"Lah, Bapak nggak ada ngasi? Katanya seminggu kemarin udah kerja di toko bahan bangunan. Ikut bantu ngangkat-ngangkat. Apa enggak ada gajinya?” Dijah berdiri menatap ibunya dengan kesal.
“Enggak kerja lagi. Cuma dua hari. Bapakmu bilang pinggangnya sakit,” sahut ibunya.
“Lebih sakit mana dengan perut kelaparan? Kok, ada laki-laki yang nggak doyan kerja. Tidur terus juga capek.”
“Jangan ngomel-ngomel di sini—”
“Ibu kalau bela Bapak enggak pernah mikirin perasaan aku. Aku ngasi belanja tiap hari karena Dul di sini. Bukan untuk ngasi makan Bapak yang masih sehat dan sanggup kerja. Aku kira yang aku lebihin bisa disimpen. Taunya habis. Giliran perlu pinjam seratus ribu aja enggak ada,” ketus Dijah.
“Gimana enggak habis? Kakang-kakangmu enggak pernah mau ngasi uang. Padahal cuma buat ngisi perut orang tuanya. Apa gunanya punya anak kalau enggak ada yang bisa bantu orang tua? Semuanya pelit,” sergah ibunya.
“Itu urusan Ibu dengan Kakang. Ibu dan Bapak orang tua mereka. Pergi ngomong sendiri sana. Jangan ngomelnya cuma aku yang denger. Giliran orangnya dateng ke sini, ngeladeninya kayak ngeladeni menteri dateng.”
“Ketimbang ngomel-ngomel buang waktu, mending kamu pinjem sama orang.”
“Pinjem sama siapa? Apa ada orang yang percaya kalau orang sesulit aku hidupnya mau pinjam uang? Bahkan orang yang sama melaratnya dengan aku, enggak suka denger cerita kemelaratanku. Apalagi orang kaya. Ya, udah. Aku pergi. Percuma punya keluarga,” sungut Dijah, meninggalkan dapur.
Ketika melintasi ruang keluarga yang merangkap sebagai ruang tamu, Dul menarik lengan ibunya. “Mau ke mana?” Dul sengaja berucap pelan seraya melirik ke dapur. Khawatir Mbah Wedok mendengar pembicaraan mereka dan ikut menimpali. Ia tak mau melihat ibunya kembali adu mulut.
“Mau kerja,” jawab Dijah. “Memangnya kenapa? Kamu udah makan, kan? Kalau udah makan sekarang tidur siang. Jangan main-main di luar, panas.”
“Mau ikut Ibu kerja,” jawab Dul.
“Ikut kerja gimana? Jangan gitu, Dul. Ibu sekarang buru-buru. Kamu jangan minta yang aneh-aneh. Ya, udah. Ibu mau belanja dagangan. Di lapangan besar ada demo buruh. Ibu mau dagang air mineral.”
“Biar Ibu ada yang nemenin. Aku lagi mau sama Ibu.” Dul kembali melirik ke dapur.
Dijah menghela napas dan ikut melirik dapur. “Di luar panas.”
“Aku ada topi.” Dul tak melepaskan tatapan dari ibunya. Ingin membuat ibunya mengerti kalau siang itu dia benar-benar mau ikut.
“Ambil topinya,” pinta Dijah.
Dul cepat-cepat ke sudut ruangan menuju laci kontainer warna-warni yang terletak di sebelah televisi. Hanya empat laci kontainer yang dimilikinya sebagai harta benda. Beberapa potong pakaian bepergian, baju-baju rumah, serta bedak dan minyak telon yang dibelikan ibunya. Ia mengeluarkan sebuah topi dari laci paling bawah dan memakainya.
“Sudah, Bu,” ujar Dul, mengusap mukanya agar terlihat lebih segar.
“Sebentar, Ibu isi air minum dulu.”
Dul pergi keluar rumah dan memakai sandal. Tak ingin berlama-lama di dalam karena bisa saja ibunya berubah pikiran karena ucapan Mbah Wedok. Ternyata kekhawatirannya tak terbukti. Tak lama ibunya keluar seraya memasukkan botol air minumnya ke dalam tas kanvas, lalu menyandangnya.
“Jangan rewel, ya, Dul. Ibu mau nyari tambahan buat kamu masuk TK.”
“TK-nya mahal?” tanya Dul, mendongak untuk melihat wajah ibunya. Wanita itu sedang menggenggam tangannya dan mereka beriringan keluar gang.
“Sebenarnya enggak mahal, enggak murah juga. Tapi buat kita uangnya yang sulit.” Dijah tertawa.
“Yang murah aja enggak apa-apa,” kata Dul menunduk. Merasa tak enak kalau ibunya harus keluar banyak uang demi kesenangannya masuk TK. Pemandangan anak-anak bermain dan bersenda gurau di halaman sebuah TK memang sangat menggiurkan baginya.
“Mau murah atau mahal, yang tugas cari uang itu Ibu. Kamu enggak usah mikir itu. Harusnya juga enggak perlu ikut siang ini.”
Dul diam saja. Mengikuti langkah kaki ibunya menyusuri tepian jalan raya dan masuk ke sebuah toko.
“Tunggu di sini. Di dalam banyak orang,” kata Dijah pada Dul.
Seorang pria mengeluarkan dua kardus air mineral serta sebungkus besar tisu yang berisi empat lusin tisu kering berukuran kecil dan meletakkannya di teras toko. Ibunya terlihat mengangsurkan lembaran uang dari dompet kecil dan berterima kasih saat keluar toko.
“Ayo, berangkat. Semoga angkot enggak rame isinya.”
Angkot yang mereka tumpangi ternyata hanya berisi tiga orang. Dul duduk di sebelah Dijah seraya mendekap sebungkus besar tisu.
Lapangan besar tempat berlangsungnya demo masih diramaikan orang-orang. Tapi sebagian sudah mulai bergerak ke pinggiran lapangan untuk mencari tempat teduh. Dijah menurunkan dagangannya ke tepi jalan dan mengangkatnya satu persatu. Dul mengikuti ke mana langkah ibunya dan menjaga satu kardus air mineral saat kardus lainnya sedang diambil.
Siang itu, Dul belajar nilai lembaran uang yang diberikan ibunya saat ia merengek meminta jajan. Berbekal dua botol air mineral, ibunya ke sana kemari menawarkan dagangan. Ibunya sangat gigih dan percaya diri. Bahkan saat beberapa pria berkata bahwa ibunya cantik dan tak pantas berdagang di bawah terik matahari, ibunya terlihat santai menanggapi.
“Dul, tisunya sisa berapa?” tanya Dijah.
Pelan-pelan Dul menghitung sisa tisu yang dipegangnya. Beberapa kali tadi ia sempat menjual beberapa karena ada yang bertanya langsung padanya saat ia sibuk melihat ibunya. Hari beranjak sore. Matanya sedikit mengantuk dan perutnya mulai lapar. Dalam hati ia meringis. Mengumpulkan tekad kalau ia tak akan memberitahu ibunya. Ia meyakinkan diri bisa menahan lapar sampai tiba di rumah dan makan malam.
“Ibu enggak capek?” tanya Dul. Dijah tertawa kecil dan berjalan mendekat.
“Demonya sudah mau selesai. Air mineralnya sisa sedikit lagi. Itu harus habis. Biar ada keuntungannya. Nih, tadi ada yang enggak mau dikasi kembalian. Ibu dapet uang lebih. Lumayan,” kata ibunya.
Dul melirik kardus air mineral yang tersisa tujuh botol lagi. Sedikit lagi, dan isi lapangan itu mulai menyusut. Hanya tinggal sebagian orang yang tersisa. Duduk berkelompok-kelompok sambil bertukar cerita.
“Kalau enggak habis, ibu rugi?” tanya Dul lagi, berusaha untuk menenangkan kekhawatirannya.
“Enggak rugi. Ibu udah untung sedikit. Yang tujuh botol sisa keuntungan kita. Tisu sisa empat, ya? Enggak apa-apa. Nanti kalau enggak habis bisa disimpan. Enggak perlu cemas. Tuhan udah menebar seluruh rezekinya ke muka bumi dengan adil. Tinggal kita yang harus usaha buat ngumpulinnya. Kalau kita dikasi rezeki lebih, itu artinya kita bisa berbagi biar rezeki itu merata.”
Dul duduk di tepi lapangan mendengarkan ucapan ibunya dengan mata sedikit terkantuk karena sepoi angin sore.
“Kamu laper? Ngantuk, ya?” tanya Dijah.
"Enggak laper,” sahut Dul.
“Berarti kamu laper. Jawabannya itu duluan,” ujar ibunya terkekeh.
Percakapan mereka terhenti sejenak karena tiga orang pria berjalan mendekati sambil membawa kantong plastik besar.
“Berdua aja, Bu? Kita bagiin ini, ya … peserta demonya sudah banyak yang pulang. Itu dagangannya, ya? Sini kita borong. Buat tambahan air minum. Soalnya isi nasi kotak Cuma air mineral gelas.”
Dul melihat ibunya sempat terbengong beberapa saat ketika menerima empat nasi kotak dari salah seorang pria muda. Pria lainnya mengangsurkan uang dan membeli sisa dagangan mereka.
“Terima kasih, Pak. Murah rejekinya,” kata Dijah dengan mata berbinar.
“Sama-sama, Bu ….”
Tiga pria pergi berlalu dan ibu anak itu diam saling bertatapan. Dul merasa sore itu mendapat durian runtuh.
“Lihat, kan? Kita enggak perlu cemas soal rezeki. Ini rezeki kamu, Dul. Ibu dagang sendirian malah enggak pernah dapat nasi kotak rumah makan mahal. Ayo, kita lihat isinya.”
Dul tersenyum sumringah dan mengangguk mantap. Menerima sekotak nasi yang diangsurkan ibunya dan mengintip ke dalam.
“Lauknya banyak, Bu. Aku langsung makan, ya?”
“Iya. Kita langsung makan. Mumpung semua orang di lapangan juga lagi makan,” sahut Dijah.
Dul melihat ibunya melepaskan perekat kardus air mineral untuk menjadikannya alas duduk. Mata ibunya yang berbinar-binar, sedikit mengurangi rasa bersalah karena biaya TK-nya. Sore itu adalah salah satu kenangan indah Dul dengan ibunya. Berdua saja duduk di tepi lapangan menikmati nasi kotak rumah makan mahal. Dagangan ibunya habis, dan biaya masuk TK-nya sedikit terbantu.
To Be Continued